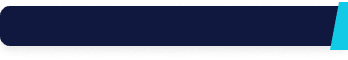Ketika Suara Pakar Tak Lagi Didengar oleh Mereka yang Tidak Pakar

Ketika Suara Pakar Tak Lagi Didengar oleh Mereka yang Tidak Pakar
A
A
A
Salah satu kasus heboh pada 2018 yang cukup meresahkan ialah isu telur plastik. Video pembuktian yang tidak saintifik tersebar melalui grup-grup chatting dan muncul di banyak beranda media sosial.
Isu itu diembuskan oleh mereka yang tidak pakar, tidak memiliki keahlian, dan sekadar cocokologi. Sayangnya, isu itu menggurita dan para pakar baik dari ahli gizi, pangan, dan peternakan seolah tak mampu menampik isu meresahkan itu. Itu hanya satu dari sekian banyak fenomena dunia modern yang menandakan Matinya Kepakaran.
Tom Nichols dalam buku ini mengupas bagaimana itu bisa terjadi, apa efeknya baik dalam skala domestik maupun dunia. Memang sampel yang digunakan dalam pembahasan adalah Amerika Serikat.
Namun, tidak menutup kemungkinan pembahasan ini bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian di Indonesia mengingat di negara kita pun pakar mulai tak lagi didengar. Suara-suara para pakar hampir dikesampingkan dewasa ini. Di tengah laju informasi yang membadai, masyarakat cenderung memilih mencari jawaban atas pertanyaan di mesin perambah secara daring.
Tidak seperti ilmu pengetahuan yang teruji secara saintifik, informasi-informasi tersebut lebih cenderung subjektif dan asal tempel. Tak kuasanya membendung informasi ini, membuat ilmuwan tak bertaji menghadapi pseudosains atau berita hoaks yang menjamur di masyarakat.
Internet hanya dapat mengubah pikiran seseorang dari “tidak memiliki pendapat” menjadi “memiliki pendapat yang sesat”, demikian bunyi hukum Pommer dalam menyikapi internet. Era informasi modern bukan hanya menciptakan lompatan dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memberi jalan memperkuat kekurangan manusia.
Internet menawarkan kebebasan akses informasi. Namun, lantaran “sifat kebebasan” itulah, segala informasi yang membanjir di internet harus selalu dikroscek. Berbeda dengan jurnal atau karya tulis ilmiah yang dapat kita telusuri sumber dan citasi ke pakar lain, sumber informasi— Wikipedia misalnya pengubahan dipasrahkan kepada pengunjung dan tidak bisa dilacak sumber informasi.
Jadilah internet membuat manusia terkungkung ketidaktahuan, yang dibalut kaya informasi keliru. Pakar dan “pakar semu” di internet memiliki perbedaan. Nichols menyebut keahlian hakiki sebagai jenis pengetahuan yang diandalkan orang lain dan bersifat tidak terukur.
Seorang pakar, misalkan ahli gizi atau pengacara, haruslah memiliki perpaduan empat hal: pendidikan tinggi, bakat kuat, kaya pengalaman, dan pengakuan dari rekan sejawat. Empatnya tidak dijamin oleh dunia maya. Namun, jangan buru-buru mengambinghitamkan internet dan arus deras informasi.
Internet hanya satu faktor mengapa suara pakar tak lagi didengar. Tom Nichols mengendus sebab akut lain mengapa para pakar hampir-hampir mati di tengah masyarakat awam. Yang harus dicurigai selanjutnya adalah bagaimana isi pemberitaan dan cara menyajikan beritanya.
Dalam teori Pareto, 8/2, disebutkan bahwa dari seluruh pekerjaan hanya 20% yang paling diingat. Kaitannya dengan suara para pakar adalah pemberitaan lebih menyoroti bila ada kesalahan prediksi atau pendapat dari pakar. Para pakar memang bukan Tuhan yang mutlak sempurna.
Dan, titik kelemahan ini yang kemudian diumbar habis-habisan oleh media hingga cara pandang masyarakat mulai bergeser. “Mengapa harus mengimani yang diucapkan oleh para ahli yang keliru?” Semakin kronis ketika kesuksesan para pakar pun tak menempati berita arus utama, cenderung tidak diperhatikan, atau sekadar ditempatkan dalam pojok kecil di halaman pungkasan media massa.
Semakin kisruhlah masyarakat memandang suara pakar. Bukti paling nyata yang kerap kita saksikan adalah tidak jarang nonpakar justru mendebat pakar dan semakin membuktikan ketidakta huannya.
Benar apa yang disampaikan oleh David Dunning dan Justin Krunger, peneliti psikologi dari Cornell University, bahwa semakin bodoh Anda, semakin Anda yakin Anda sebenarnya tidak bodoh. Meskipun ada pakar yang dibesarkan oleh pengalaman. Namun, syarat utama seorang pakar adalah pendidikan yang mumpuni.
Seorang dokter haruslah lahir dari bangku fakultas kedokteran. Seorang pengacara berbakat bukan yang lulus dari fakultas teknik. Ini adalah hukum mutlak untuk menjadi seorang pakar. Nichols menduga universitas juga berperan dalam matinya kepakaran.
Kampus tak ubahnya rekanan bisnis yang menjual ijazah dan gelar. Budaya pendidikan yang mengantarkan mahasiswa menjadi calon pakar dan menghargai suara pakar tak lagi diadiluhungkan. Perguruan tinggi kini dipasarkan sebagai paket liburan selama beberapa tahun, bukan sebagai kontrak dengan institusi dan dosen untuk perjalanan pendidikan.
(h. 87) Selain tiga faktor eksternal tersebut, ada satu faktor internal yang Nichols deteksi sebagai titik awal matinya kepakaran, yakni dasar sifat manusia, egois. Sifat ini batu sandungan pertama yang harus dienyahkan.
Kebanyakan dari kita bersikap, “Saya melihat sesuatu dari sumber yang kebetulan saya sukai dan sumber itu mengatakan sesuatu yang ingin saya dengar.” Ilusi pribadi membuat kita hanya mau mendengar pendapat yang membenarkan keyakinan kita dan cenderung menampik yang berseberangan.
Itu kodrat. Tetapi, demi kepakaran dan kehidupan berkelanjutan, sikap itu harus dinormalisasi dan dirasionalisasi. Ada sebuah budaya di Jepang yang menarik untuk dicontoh. Seorang pakar akan diberi gelar sensei.
Suaranya didengar, kehadirannya dihormati, dan membungkuk saat bersua. Tidak melulu profesor di menara gading, bahkan dokter gigi, guru SMA, hingga guru TK pun diberi gelar sensei.
Begitulah seharusnya seorang ahli dihormati begitu tinggi meski seorang ahli menerima koreksi bila keliru. Karena, kelirunya para ahli lebih baik daripada pendapat nonpakar yang kebetulan benar.
Isu itu diembuskan oleh mereka yang tidak pakar, tidak memiliki keahlian, dan sekadar cocokologi. Sayangnya, isu itu menggurita dan para pakar baik dari ahli gizi, pangan, dan peternakan seolah tak mampu menampik isu meresahkan itu. Itu hanya satu dari sekian banyak fenomena dunia modern yang menandakan Matinya Kepakaran.
Tom Nichols dalam buku ini mengupas bagaimana itu bisa terjadi, apa efeknya baik dalam skala domestik maupun dunia. Memang sampel yang digunakan dalam pembahasan adalah Amerika Serikat.
Namun, tidak menutup kemungkinan pembahasan ini bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian di Indonesia mengingat di negara kita pun pakar mulai tak lagi didengar. Suara-suara para pakar hampir dikesampingkan dewasa ini. Di tengah laju informasi yang membadai, masyarakat cenderung memilih mencari jawaban atas pertanyaan di mesin perambah secara daring.
Tidak seperti ilmu pengetahuan yang teruji secara saintifik, informasi-informasi tersebut lebih cenderung subjektif dan asal tempel. Tak kuasanya membendung informasi ini, membuat ilmuwan tak bertaji menghadapi pseudosains atau berita hoaks yang menjamur di masyarakat.
Internet hanya dapat mengubah pikiran seseorang dari “tidak memiliki pendapat” menjadi “memiliki pendapat yang sesat”, demikian bunyi hukum Pommer dalam menyikapi internet. Era informasi modern bukan hanya menciptakan lompatan dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memberi jalan memperkuat kekurangan manusia.
Internet menawarkan kebebasan akses informasi. Namun, lantaran “sifat kebebasan” itulah, segala informasi yang membanjir di internet harus selalu dikroscek. Berbeda dengan jurnal atau karya tulis ilmiah yang dapat kita telusuri sumber dan citasi ke pakar lain, sumber informasi— Wikipedia misalnya pengubahan dipasrahkan kepada pengunjung dan tidak bisa dilacak sumber informasi.
Jadilah internet membuat manusia terkungkung ketidaktahuan, yang dibalut kaya informasi keliru. Pakar dan “pakar semu” di internet memiliki perbedaan. Nichols menyebut keahlian hakiki sebagai jenis pengetahuan yang diandalkan orang lain dan bersifat tidak terukur.
Seorang pakar, misalkan ahli gizi atau pengacara, haruslah memiliki perpaduan empat hal: pendidikan tinggi, bakat kuat, kaya pengalaman, dan pengakuan dari rekan sejawat. Empatnya tidak dijamin oleh dunia maya. Namun, jangan buru-buru mengambinghitamkan internet dan arus deras informasi.
Internet hanya satu faktor mengapa suara pakar tak lagi didengar. Tom Nichols mengendus sebab akut lain mengapa para pakar hampir-hampir mati di tengah masyarakat awam. Yang harus dicurigai selanjutnya adalah bagaimana isi pemberitaan dan cara menyajikan beritanya.
Dalam teori Pareto, 8/2, disebutkan bahwa dari seluruh pekerjaan hanya 20% yang paling diingat. Kaitannya dengan suara para pakar adalah pemberitaan lebih menyoroti bila ada kesalahan prediksi atau pendapat dari pakar. Para pakar memang bukan Tuhan yang mutlak sempurna.
Dan, titik kelemahan ini yang kemudian diumbar habis-habisan oleh media hingga cara pandang masyarakat mulai bergeser. “Mengapa harus mengimani yang diucapkan oleh para ahli yang keliru?” Semakin kronis ketika kesuksesan para pakar pun tak menempati berita arus utama, cenderung tidak diperhatikan, atau sekadar ditempatkan dalam pojok kecil di halaman pungkasan media massa.
Semakin kisruhlah masyarakat memandang suara pakar. Bukti paling nyata yang kerap kita saksikan adalah tidak jarang nonpakar justru mendebat pakar dan semakin membuktikan ketidakta huannya.
Benar apa yang disampaikan oleh David Dunning dan Justin Krunger, peneliti psikologi dari Cornell University, bahwa semakin bodoh Anda, semakin Anda yakin Anda sebenarnya tidak bodoh. Meskipun ada pakar yang dibesarkan oleh pengalaman. Namun, syarat utama seorang pakar adalah pendidikan yang mumpuni.
Seorang dokter haruslah lahir dari bangku fakultas kedokteran. Seorang pengacara berbakat bukan yang lulus dari fakultas teknik. Ini adalah hukum mutlak untuk menjadi seorang pakar. Nichols menduga universitas juga berperan dalam matinya kepakaran.
Kampus tak ubahnya rekanan bisnis yang menjual ijazah dan gelar. Budaya pendidikan yang mengantarkan mahasiswa menjadi calon pakar dan menghargai suara pakar tak lagi diadiluhungkan. Perguruan tinggi kini dipasarkan sebagai paket liburan selama beberapa tahun, bukan sebagai kontrak dengan institusi dan dosen untuk perjalanan pendidikan.
(h. 87) Selain tiga faktor eksternal tersebut, ada satu faktor internal yang Nichols deteksi sebagai titik awal matinya kepakaran, yakni dasar sifat manusia, egois. Sifat ini batu sandungan pertama yang harus dienyahkan.
Kebanyakan dari kita bersikap, “Saya melihat sesuatu dari sumber yang kebetulan saya sukai dan sumber itu mengatakan sesuatu yang ingin saya dengar.” Ilusi pribadi membuat kita hanya mau mendengar pendapat yang membenarkan keyakinan kita dan cenderung menampik yang berseberangan.
Itu kodrat. Tetapi, demi kepakaran dan kehidupan berkelanjutan, sikap itu harus dinormalisasi dan dirasionalisasi. Ada sebuah budaya di Jepang yang menarik untuk dicontoh. Seorang pakar akan diberi gelar sensei.
Suaranya didengar, kehadirannya dihormati, dan membungkuk saat bersua. Tidak melulu profesor di menara gading, bahkan dokter gigi, guru SMA, hingga guru TK pun diberi gelar sensei.
Begitulah seharusnya seorang ahli dihormati begitu tinggi meski seorang ahli menerima koreksi bila keliru. Karena, kelirunya para ahli lebih baik daripada pendapat nonpakar yang kebetulan benar.
(don)